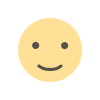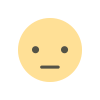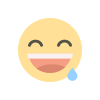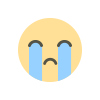Pemenang Kompetisi
Pemenang Kompetisi
Surakarta, Tionghoa, dan Pribumi: Menelisik Jejak Konflik dan Jalan Damai
Artikel ini membahas konflik etnis antara Tionghoa dan pribumi di Surakarta dari masa kolonial hingga kerusuhan besar pada tahun 1998. Artikel ini juga menyoroti upaya perdamaian melalui pendidikan multikultural dan kolaborasi lintas etnis, termasuk peran mahasiswa dalam menciptakan harmoni.


Surakarta, yang dikenal sebagai Kota Budaya, tak hanya menyimpan harmoni tradisi, tetapi juga cerita kelam konflik sosial. Dari 1972 hingga 1998, kota ini menjadi saksi serangkaian kerusuhan yang melibatkan ketegangan antara etnis Tionghoa dan pribumi. Konflik ini tidak muncul begitu saja, melainkan dipicu oleh dinamika ekonomi, politik, dan sosial yang saling berkelindan. Di balik tragedi itu, tersimpan pelajaran penting untuk mencegah sejarah serupa terulang.
Sejarah Panjang yang Berulang
Jejak ketegangan etnis di Surakarta sebenarnya telah ada sejak masa kolonial. Salah satu peristiwa paling awal adalah Bedah Kartasura pada 1742, ketika konflik sosial dan ekonomi mencuat antara etnis Tionghoa dan pribumi Jawa. Namun, di era modern, ketegangan ini menemukan bentuk baru. Pada masa Orde Baru, penguasaan sektor ekonomi oleh pengusaha Tionghoa kerap menjadi bahan bakar kecemburuan sosial, sementara kebijakan diskriminatif pemerintah memperkeruh suasana.
Ketimpangan ini menciptakan jurang tajam antara komunitas Tionghoa yang dianggap elite ekonomi dan masyarakat pribumi yang sebagian besar bekerja di sektor informal. Diskriminasi politik dan sosial terhadap Tionghoa semakin memperburuk hubungan antar kelompok.
1972: Kerusuhan dari Insiden Kecil
Kerusuhan pertama terjadi pada 1972, dipicu oleh insiden sederhana—perselisihan antara seorang penarik becak dengan warga keturunan Arab terkait pembayaran jasa. Ketika penarik becak tersebut ditemukan tewas, kemarahan massa membara. Dalam waktu singkat, provokasi menyebar, dan kerusuhan meluas hingga ke komunitas Tionghoa.
Kerusuhan ini menjadi gambaran betapa rapuhnya hubungan sosial di tengah ketimpangan. Insiden kecil dapat memicu amarah besar ketika ketegangan telah lama terpendam.
1980: Senggolan Sepeda yang Memicu Amuk Massa
Delapan tahun berselang, konflik serupa pecah dengan pola yang mirip. Berawal dari senggolan sepeda antara Supriyadi alias Pipit, seorang pelajar, dan Kicak alias Maryono, seorang pemuda keturunan Tionghoa, perkelahian kecil ini berubah menjadi demonstrasi.
Awalnya, hanya puluhan siswa yang turun ke Jalan Urip Sumoharjo untuk memprotes insiden tersebut. Namun, massa yang terprovokasi dengan cepat memperbesar skala kerusuhan, menyebabkan kekerasan meluas terhadap komunitas Tionghoa.
1998: Krisis yang Membuka Luka Lama
Puncak dari rangkaian konflik ini terjadi pada Mei 1998, di tengah krisis moneter dan politik yang mengguncang Indonesia. Surakarta menjadi salah satu kota yang paling terdampak oleh kerusuhan rasial anti-Tionghoa.
Penjarahan, pembakaran toko, hingga kekerasan fisik menimpa komunitas Tionghoa di Surakarta. Pola kekerasan yang terjadi menunjukkan kemungkinan adanya kelompok yang sengaja memprovokasi situasi, meski hingga kini hal itu masih menjadi misteri. Kerusakan ekonomi dan sosial akibat peristiwa ini meninggalkan luka mendalam yang belum sepenuhnya sembuh.

Mahasiswa dan Peran Mereka
Di tengah konflik ini, mahasiswa sering muncul sebagai agen perubahan. Pada 1998, mahasiswa menjadi ujung tombak gerakan reformasi, menyerukan keadilan sosial dan demokrasi. Namun, peran mereka dalam konflik rasial tetap menjadi perdebatan.
Sebagian mahasiswa terlibat dalam advokasi untuk korban, memberikan bantuan kemanusiaan, dan mempromosikan dialog lintas etnis. Namun, tekanan politik Orde Baru membatasi ruang gerak mereka, bahkan dalam beberapa kasus, mahasiswa justru terseret dalam arus provokasi yang memperkeruh situasi.
Masa Depan: Pendidikan untuk Harmoni
Tragedi ini menjadi pengingat bahwa toleransi tidak tumbuh dengan sendirinya. Surakarta, sebagai Kota Budaya, memiliki tanggung jawab besar untuk merekatkan kembali hubungan antar komunitas. Pendidikan multikultural, pemberdayaan ekonomi, dan dialog lintas etnis adalah kunci untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.
Di Universitas Sebelas Maret (UNS), khususnya Fakultas Teknik, cerita berbeda mulai terukir. Fakultas ini menjadi contoh nyata bagaimana keberagaman bukanlah hambatan. Mahasiswa dari berbagai latar belakang suku dan negara, seperti Papua, Kalimantan, Jawa, hingga Timur Tengah, bekerja sama dalam proyek dan kegiatan sosial.
Dalam sebuah program kerja praktek, misalnya, mahasiswa dari Papua, Jawa, dan Arab bersatu untuk merancang teknologi energi terbarukan. Kolaborasi lintas budaya ini membuktikan bahwa keberagaman memperkaya hasil akhir. Kegiatan seni dan budaya di Fakultas Teknik juga menjadi ruang untuk mempererat hubungan, seperti pameran kaligrafi Arab, tari Papua, hingga gamelan Jawa yang tampil berdampingan.
Menatap ke Depan
Surakarta adalah simbol dinamika Indonesia yang penuh warna. Konflik masa lalu menjadi pengingat bahwa harmoni perlu diperjuangkan dengan dialog, kesetaraan, dan penghormatan terhadap keberagaman. Kini, mahasiswa—sebagai generasi penerus—memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga perdamaian dan memastikan perbedaan menjadi kekuatan.
Surakarta, Tionghoa, dan pribumi: mereka bukan musuh, melainkan potongan puzzle yang jika dirangkai bersama akan menciptakan gambaran masyarakat yang lebih kuat dan inklusif.


 Rohmat Aji Pamungkas | Universitas Sebelas Maret
Rohmat Aji Pamungkas | Universitas Sebelas Maret